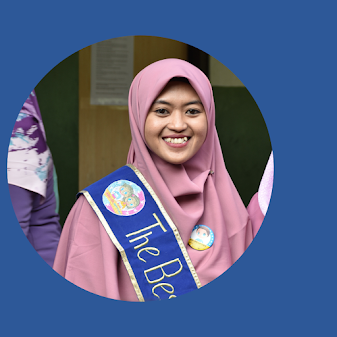Archive for September 2016
Belajar Mengalahkan Diri Sendiri
“Karena manusia bukan Tuhan yang
tahu segala yang tersimpan dalam hati dan pikiran. Maka katakanlah, agar orang
lain mengerti dan setiap masalah terselesaikan tanpa adanya masalah baru”
(Anonim)
 |
| Satu setengah tahun lalu saat menghadiahi Emak sarjana pendidikan sekaligus menjadi sarjana pertama dalam keluarga :) |
Sebagai
perempuan termuda di rumah, bisa dibilang saya adalah perempuan yang paling
keras kepala. Tidak kalah dengan keras kepalanya Emak. Meskipun sama-sama keras
kepala, kami memiliki satu perbedaan. Emak menunjukkan kekeraskepalaannya
dengan ucapan, sedangkan saya menunjukkan kekeraskepalaan saya dengan diam.
Terbayang
bagaimana jika kami sedang marah? Ya, emak akan terus berbicara dan saya akan
terus diam untuk menunjukkan kemarahan saya. Buruknya lagi, saya baru saja
melewati masa marahan saya dengan Emak di hari ini, tepat di Hari Raya Idul
Adha ini.
Semua ini
bermula dari argument kami tentang pembagian tugas di rumah. Emak dan bapak
memiliki usaha kecil-kecilan berjualan soto di salah satu perkantoran di
Jakarta. Sementara itu saat ini saya sedang bekerja sebagai asisten dosen di
salah satu kampus swasta, mengajar private anak berkebutuhan khusus pada malam
hari, sambil belajar untuk mempersiapkan kuliah di Eropa. Sayangnya, meskipun
saya sudah berusaha untuk mendapatkan beasiswa keluar negeri, tapi Emak dan
Bapak belum meresui saya. Hingga kekecewaan saya memuncak saat saya memilih
belajar dibandingkan membantu kakak di dapur untuk keperluan dagang esok
harinya.
Emak marah.
Seperti biasa membandingkan saya dengan anak tetangga atau sepupu yang lainnya.
Lalu semuanya merambat pada kesalahan-kesalahan sebelumnya yang kembali
disebut. Alhasil, malam itu saya meninggalkan buku-buku saya dan mengerjakan
apa yang Emak minta, meskipun sambil sedikit menangis.
Saya
menangis bukan karena diminta bekerja membantu menyiapkan dagangan. Saya
menangis karena saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan dengan dagangan
yang selama ini diurus oleh Emak dan kakak saya. Ditambah lagi Emak yang
memberikan perintah berurutan. Saya selalu merasa bingung jika diberi perintah
berurutan atau diberikan daftar perintah lebih dari dua secara langsung dan
bersamaan. Tapi Emak dan orang-orang rumah lainnya tidak memahami saya. Yang
saya tahu –berdasarkan ilmu pendidikan khusus yang sedang saya geluti saat ini,
kurang mampu menerima perintah secara berurutan adalah salah satu tanda
disleksia. Setelah saya telusuri dan ingat-ingat lebih jauh lagi, memang sejak
kecil saya tidak bisa diberi perintah berurutan. Kalaupun saya melakukannya,
saya akan melakukannya sambil menangis kebingungan karena tidak paham mana yang
harus dilakukan duluan.
Lanjut pada
cerita saya pada malam itu. Semuanya saya coba lakukan seperti apa yang
dilakukan Emak dan kakak. Demikian pula keesokan harinya, saya melakukan apa
yang seharusnya saya lakukan sebagai pengajar sekaligus anak. Mengajar,
menyapu, mengepel, dan menyeterika pakaian saya lakukan dengan cukup baik hari
ini.
Sayangnya,
saat saya bangun pukul setengah dua malam untuk shalat, saya mendengar Emak
sedang mengomel sendirian di dapur. Beberapa omelannya tentang pekerjaan untuk
keperluan berdagang esok hari yang belum selesai dikerjakan oleh kami
anak-anaknya. Sisanya adalah kemarahan Emak kepada saya. Refleks saat itu juga
saya tidak jadi beranjak keluar kamar. Saya malah menangis semalaman hingga
mata saya sembab.
Pagi
harinya saya memutuskan absen dari tugas harian saya di rumah. Rumah yang sudah
dipel dan piring kotor yang sudah saya bersih tidak menjadi pemandangan pagi
sebelum saya berangkat bekerja. Saya hanya diam di kamar, memikirkan omelan
Emak malam itu dan pergi bekerja di saat saya harus pergi.
Sore
harinya saya habiskan waktu di kamar. Saya sama sekali tidak berkumpul dengan
keluarga lainnya di ruang menonton. Saya memutuskan tidak berbicara pada yang
lainnya meskipun Bapak masih memutuskan berbicara dengan saya. Emak, memutuskan
mengikuti apa yang sudah saya mulai. Jika di rumah, yang saya lakukan hanya
membaca buku-buku pendidikan khusus atau mempersiapkan ujian IELTS. Oh iya,
Di tengah
doa setelah shalat, saya teringat salah satu ajaran Rasulullah bahwa jika seorang
muslim sedang marah, maka dilarang saling mendiamkan lebih dari tiga hari.
Mengapa tiga hari? Karena selama tiga hari itu sejatinya waktu yang cukup untuk
menghilangkan amarah dan selebihkan bukan amarah saat bertengkar yang berperan
tapi amarah lain, ego lain yang mengambil alih.
Mengingat
hal itu, saya memikirkan cara bagaimana melakukan aktivitas seperti sedia kala.
Jika saya sudah marah sejak Kamis pagi, dan memilih tidak berbicara sejak
Jumat, maka Minggu adalah hari terakhir saya untuk mendiamkan mereka. Tapi saya
tidak ingin dianggap salah oleh Emak. Saya juga tidak mau melakukan itu
terlebih dahulu.
Beruntung
ada adik Emak bertamu pada MInggu sore. Saya selalu menutupi konflik keluarga
di depan orang lain, termasuk di depan keluarga besar. Jadi selama adik Emak
bertamu, saya bersikap seperti biasa, keluar kamar, berbicara dengan yang
lainnya, dan ikut bergabung di ruang tamu. Tapi setelah adik Emak pulang, saya
kembali ke kamar. Saya tidak tahu harus memulai dari mana dan saya justru
kembali ke kamar, mengurung diri hingga hari raya tiba. Saya juga memutuskan untuk
mogok makan sejak sabtu sore. Emak tahu itu.
Malam itu
saya menangis lagi sendirian. Saya bingung ingin memulai dari mana. Yang bisa
saya ucapakan di antara takbir hari raya idul adha adalah “Kapan ini akan
berakhir, ya Allah!”
***
Saya tidak
shalat hari raya karena saya sedang dalam masa menstruasi. Saya menghabiskan
pagi hanya di dalam kamar sementara Emak dan kakak saya sibuk di dapur sejak Minggu
pagi untuk menyiapkan hari raya.
Tepat pukul
setengah delapan pagi, setelah Emak pulang dari shalat hari raya, Emak masuk ke
kamar saya. Beliau membangunkan saya dengan menggoyang-goyangan badan saya
sambil berkata, “Bangun, Nak. Ini hari raya. Ngapain kamu marah kayak begitu?”
Saya tidak
menjawab dan lagi-lagi hanya menangis.
“Mau sampai
kapan kamu kayak gini? Ini hari raya. Ayo keluar!” Emak masih menggoyangkan
tubuh saya sementara saya diam dan tidak berkutik sedikitpun.
Setengah
jam berlalu dan saya memutuskan bangun. Saya kembali ke laptop dan membuka file
palajaran individual yang saya punya. Tidak lama kemudian Emak datang lagi
menghampiri saya.
“Makan
sana! Emak masak-masak dari kemarin. Tolong ubah sikap kamu. Ini hari raya.
Saling memaafkan,” kata Emak di belakang saya. Saya hanya lurus menatap laptop
denga mata berkaca-kaca antara marah dan keinginan untuk mengakhiri amarah.
Pukul delapan
empatlima Emak kembali dan mulai menaikkan nada suaranya. “Kamu kenapa sih?
Marah kenapa? Kenapa gak ngomong? Kenapa begini?”
“Lis gak
marah. Lis begini karena Emak yang marah duluan,” jawab saya.
“Marah yang
kapan? Emak gak marah. Kan Emak bilang kalau Lis mau belajar silakan. Gak
apa-apa. Emak gak mau Lis gagal ujian dan malah nyalahin Emak.”
“Waktu
malam Emak marahin Lis. Padahal Lis lagi tidur. Lis sedih dengerinya,”
“Astaghfirullah,
Nak. Kapan itu?”
“Tuh kan
Emak gak ngerasa ngomong. Tapi Lis ngedenger sendiri dari kamar. Lis mau shalat
tapi gak jadi gara-gara Lis denger Emak marahin Lis malem-malem,” saya semakin
menangis.
Emak terus
bertanya banyak hal tentang perilaku saya belakang. Lalu sebuah memeluk saya
sesudah berkata, “Maafin Emak ya. Maaf kalau Emak khilaf. Kesal dan bicara
kasar ke Lis. Emak gak ada maksud apa-apa,”
Saya terus
menangis. Terunduk di dalam kedua lengan saya. Emak mengangkat kepala saya.
Beliau terus berbicara.
“Lihat
Emak, Lis. Lihat Emak. Emak minta maaf ya. Lis tahu kan Emak pengin Lis sukses,
Emak khilaf ngomel karena kesel. Lihat Emak, Lis. Lihat!” Emak menangis,
meminta saya terus melihat kea rah matanya.
Saat itu
saya merasa seperti anak kecil kembali. Saya seperti anak-anak berkebutuhan
khusus yang sering saya tangani. Saya mengalami meltdown (pelampiasan amarah
dari menumpuknya kesal akan banyak hal).
Saat itulah
saya tahu bahwa saya harus mengatakan semua yang saya rasakan hingga meltdown
saya hilang. Saya mengatakan apa saja yang saya harapkan dari Emak, Bapak, dan
kakak. Termasuk berharap Emak tidak memberikan perintah berurutan atau banyak
perintah secara bersamaan. Di saat itulah saya mengatakan keinginan saya untuk
melanjutkan kuliah ke University of Birmingham sangat besar, demi Emak dan
Bapak. Termasuk mengatakan untuk tidak memikirkan pernikahan demi memikirkan
kebahagiaan Emak Bapak dan untuk mengangkat derajat keduanya di hadapan Allah
juga orang-orang yang pernah memandang rendah keluarga kami. Juga tentang
kesedihan saya selama beberapa bulan ini mengurus anak-anak jalanan sendirian
di saat beberapa teman yang saya anggap bisa mendukung justru memilih mundur.
Begitupun
Emak. Beliau mengungkapkan apapun yang beliau ingin ungkapkan. Harapan beliau
kepada saya. Doa-doa beliau kepada saya dan keluarga. Termasuk nasihat untuk focus
melanjutkan kuliah dibandingkan mengurus anak-anak jalanan sendirian.
Kami
mengakui segala kesalahan kami. Mengungkapkan kegelisahan kami satu sama lain.
Lalu mengatakan maaf dalam pelukan. Emak mencium wajah saya yang berlumuran air
mata. Meminta saya menatap wajahnya sekali lagi. Sekali lagi berbagi maaf,
tetap memeluk saya hingga saya merasa tenang dan kami sama-sama merasa lebih
baik.
***
Sebenarnya
yang ingin saya sampaikan di sini bukan bagaimana saya bermarahan dengan Emak
hingga kami berbaikan di hari raya idul adha ini. Saya ingin menyampaikan apa
yang ada di balik marah dan maaf yang kami bagi selama beberapa hari
belakangan.
Saya
pribadi merasa begitu egois ketika saya merasa menjadi yang paling tersakiti
karena omelan Emak. Saya merasa sudah cukup tertekan dengan pekerjaan di
kampus, private, pekerjaan sosial yang saya lakukan sendiri, serta pekerjaan di
rumah sebagai anak rumah tangga. Tapi saya lupa berkaca pada Emak yang saat ini
menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi Bapak yang sudah tidak sesehat
dulu. Saya lupa melihat Emak yang harus memikirkan saya, kakak dan keponakan
yang disabilitas, serta kakak pertama saya yang seorang single parent. Saya
lupa berkaca pada Emak yang harus bangun dini hari dengan menyekolahkan saya
hingga sarjana. Saya lupa pada sosok hebat yang telah menjadikan saya seperti
sekarang saya adanya. Saya lupa melihat sisi lain di rumah ini dari beliau.
Saya tersadarkan
akan hal ini karena malam harinya saya menonton live action Chibi Maruko Chan
the movie. Dalam film tersebut Maruko marah kepada ibu dan kakaknya karena ibu
membelikan pakaian baru untuk kakaknya tapi tidak untuk dirinya. Sebaliknya,
Maruko malah diberikan pakaian yang pernah dipakai kakaknya. Di bagian lain,
Maruko sedih karena kakaknya memberikan seri stiker yang sedang dikumpulkannya
kepada adik kelasnya dalam agenda “Perjalanan Pertemanan”. Saat Maruko mengadu
kepada ibunya, ibu Maruko hanya menjawab, “Ya mau bagaimana lagi. Kan sudah
diberikan ke orang lain.” Mendengar jawaban ibunya, Maruko jadi semakin sedih
dan marah kepada hampir seluruh penghuni rumah –kecuali kepada kakeknya. Tapi
di akhir cerita, kakak Maruko tetap memberikan sebuah Bulu Amal kepada Maruko
daripada kepada adik kelasnya. Kakak Maruko berkata kepada adik kelasnya bahwa
Bulu Amal adalah lambang keluarga dan bagaimanapun Maruko tetaplah keluarganya
dibandingkan dengan adik kelasnya tersebut.
Saya merasa
posisi saya cukup mirip dengan Maruko. Saat ibu Maruko merespon aduan Maruko
dengan kata “mau bagaimana lagi” adalah sebuah respon logis tetapi Maruko
menanggapinya dengan respon perasaan. Hingga akhirnya Maruko merasa ibunya
salah dan ibu Maruko menganggap Maruko salah telah marah tanpa sebab yang
jelas. Persis seperti marahnya saya kepada Emak karena Emak telah marah kepada
saya. Padahal Emak belum tentu semarah saya saat saya dimarahi oleh beliau.
Satu hal
lagi, saya sering kali merasa bahwa diri sayalah yang paling sengsara. Mungkin ini
sering dialami banyak orang, merasa bahwa dirinyalah yang ada di posisi paling
buruk dan terpuruk sendirian. Padahal, jika ingin membuka diri sedikit saja,
kita akan tahu bahwa kesulitan bukan hanya milik kita sendiri. Kesulitan dan
keresahan adalah milik banyak orang. Tapi membuka diri adalah pilihan beberapa
orang untuk menyadari. Saya pun baru menyadari bahwa kesusahan yang saya alami tidak
seberapa besar dibandingkan apa yang harus Emak hadapi, terutama saat
berhadapan dengan saya.
Lalu di
mana letak kesalahan yang sesungguhnya? Pada gengsi kita. Itulah jawaban yang
saya punya saat ini.
Saya gengsi
untuk bertanya langsung maksud amarah Emak malam itu dan saya malah memilih
diam di kamar sambil menangis. Saya gengsi untuk memulai percakapan setelah
tiga hari tidak berbicara. Pun saya gengsi untuk melunakkan hati saya sendiri.
Emak?
Mungkin Emak gengsi dengan diamnya saya, hingga beliau marah di belakang saya.
Bisa jadi beliau juga gengsi dengan amarahnya sendiri hingga beliau ikut
mendiamkan saya saat saya mulai memilih diam.
Kami
sama-sama gengsi untuk menunjukkan kalau kami ingin semuanya kembali seperti
sedia kala. Kami nyatanya gengsi mengakui bahwa kami saling membanggakan,
saling menyayangi, dan ingin kembali seperti sedia kala.
Lalu gengsi
itu hilang saat kami sama-sama mengungkapkan apa yang sebenarnya kami rasakan.
Keterbukaan akan apa yang kami alami adalah pemutus tali gengsi tersebut. Saat
bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kami harapkan, dan apa
yang tidak kami harapkan, semua amarah itu perlahan hilang bersama hilangnya
gengsi kami untuk saling terbuka. Kemudian, hilanglah gengsi kami untuk saling
meminta maaf meskipun saat itu wajah kami jelek dan beringus karena sama-sama
sedang menangis.
Benar apa
kata seseorang, kejujuran adalah kunci dari sebuah hubungan. Jujur tentang apa
yang kita rasakan dan jujur terhadap apa yang kita harapkan benar-benar menjadi
inti dari kebersamaan. Pastinya, jujur pun perlu diikuti oleh pembicaraan untuk
menemukan solusi bersama.
Untuk
sebuah hubungan ibu dan anak, bapak dan anak, guru dan murid, teman, sahabat,
dan kekasih. Sejatinya tidak ada yang akan salah paham jika kita mau
mengatakannya. Tidak ada yang tersakiti jika kita mau mengalah tapi tidak pada
ego dan gengsi diri sendiri.
Untuk Emak
yang telah mengajarkan arti perjuangan. Lis percaya, kita masih bisa saling
berpelukan, tersenyum, dan tertawa bersama hingga suatu hari nanti Emak melihat
Lis menjadi seorang sarjana untuk kedua dan ketiga kalinya, bersama dengan
suami dan anak-anak Lis. Semoga Allah senantiasa menyehatkan dan menjaga Emak Bapak di manapun kalian berada. Amiin.
“Mengalahlah
pada setiap orang hingga tidak ada lagi yang mampu mengalahkanmu”
(Anonim)
Jakarta, 13
September 2016
0:49 pagi
Melly; Kurungan Harapan (2)
Tiga tahun
lalu saat saya masih kuliah, seorang ibu datang ke rumah saya. Beliau bertamu ketika
saya sedang membuang sampah selapas menyapu teras rumah di sore hari.
“Kak Lis,”
panggilnya dari balik pagar rumah saya.
Saat saya
menoleh, dia mendekati saya. Beliau tersenyum meski raut wajahnya tidak bisa
menutupi kelelahannya.
Namanya Bu
Tuti, anak seorang lelaki paruh baya yang saya kenal baik sebagai guru mengaji
di perkampungan tempat tinggal kami.
“Kak Lis
katanya ngajar di SLB ya?” tanyanya langsung.
“Saya masih
kuliah, Bu. Sambil ngajar juga. Tapi bukan di SLB,” jelas saya.
“Tapi
ngajarin anak-anak yang kayak begitu kan?” tanyanya lagi.
Saya
mengerutkan kening. Sebenarnya kata “begitu” ketika membicarakan profesi saya
adalah salah satu kata yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Kata itu
membuat seolah-olah anak-anak berkebutuhan khusus tidak memiliki kriteria lain
selain keabstrakan yang tidak terdefinisi di masyarakat. Di sisi lain,
kurangnya informasi kepada masyarakat tentang keberadaan anak-anak berkebutuhan
khusus ini menjadi salah satu sebab munculnya kata “begitu”.
“Iya kan,
Kak Lis?” tanyanya lagi dengan suara yang lebih menarik keprihatinan saya.
“Iya, saya
ngajar anak-anak yang autis. Tapi di sekolah inklusi, Bu. Sekolah umum yang
nerima anak-anak autis,” saya mencoba menjelaskan.
“Ini…,”
suaranya menggantung antara keraguan dan harapan. “Ada anak di TPA saya yang
diam terus. Gak mau berbaur dengan anak-anak lain. Kemampuannya juga di bawah
yang lain.”
“Oh, terus
gimana, Bu?” tanya saya.
“Kak Lis
bisa liatin anak itu dulu? Kali aja Kak Lis bisa nanganin anak itu,” beliau
memegang tangan saya. Sebuah kontak fisik antara guru dan wali murid ini kurang
saya sukai. Bukan karena alasan agama melainkan saya akan sulit menolak karena
ketika tangan saya disentuh, maka dengan sendirinya saya menjadi luluh untuk
melakukan sesuatu untuk anak mereka.
Saya
mengiyakan permintaannya. Membuat janji pertemuan yang ternyata tidak pernah
dapat saya tepati karena tugas-tugas di kampus yang saat itu cukup menyita
waktu.
***
Itu adalah
pertemuan pertama saya dengan orang tua Melly yang kemudian saya tahu dari Emak
bahwa yang dimaksud dengan murid TPA-nya adalah Melly. Entah kenapa Bu Tuti
menyebut anaknya sebagai muridnya. Tapi saya yakin, beliau memiliki alasan untuk
hal itu dan saat ini saya tidak terlalu mempedulikan alasan itu.
Kini
saatnya saya focus kepada Melly, membayar hutang pertemuan itu.
***
Pertemuan
kedua. Melly diantar ibunya hingga teras rumah. Tubuhnya menggelantung di
tangan ibunya, tidak mau masuk. Melly merajuk tanpa suara, kakinya yang memaku
di teraslah yang menyuarakan keengganannya masuk bersama saya. Maka dengan
terpaksa saya melepas tangannya dari tangan ibunya dan menuntunnya ke dalam
rumah.
Tangan
Melly dingin. Mungkin sepertinya selalu dingin, karena di pertemuan pertama pun
tangannya dingin. Secara fisik Melly sama seperti anak kelas tiga sekolah dasar
pada umumnya, malah tubuhnya cenderung tinggi. Tubuhnya sudah mencapai telinga
saya yang memiliki tinggi seratus lima puluh sentimeter saja. Badannya kurus
dengan kulit kuning langsat, bersih. Mata sipit dan postur tubuhnya yang sering
membungkuk adalah beberapa hal yang membuatnya agak berbada dengan anak-anak
lainnya di sekitar rumah.
***
Saya
mengajak Melly duduk bersama saya. Kami dipisahkan sebuah meja lipat bergambar
tokoh kartun Spongebob Square Pants. Saya kembali mengambil kardus berisi
buku-buku dan memintanya mengambil buku baru untuk dibaca bersama –yang kenyataannya
hanya saya yang membaca.
Melly tidak
merespon. Dia hanya menunduk. Rambutnya yang tak cukup panjang agak menjuntai,
membantunya menutup diri dari pandangan saya.
“Hari ini
kita mau mambaca buku ya mana nih?” saya bertanya.
Tetap tidak
ada respon. Saya memutuskan untuk mengambil sebuah buku tipis dari Serial
Profesi yang berjudul “Pengusaha Boneka”.
“Aku
bacakan yang ini ya. Kamu mau?”
Melly tetap
diam. Tidak ada suara. Tidak ada isyarat ataupun gesture tubuh yang menjawab
pertanyaan saya.
“Kamu suka
boneka? Aku suka boneka. Waktu aku esde, aku punya banyak boneka. Aku juga suka
bikin baju boneka sendiri. Buku yang mau kita baca ini tentang boneka loh.
Sebenarnya ini tentang pengusaha boneka. Orang yang punya banyak banget boneka.
Mau tahu gak kenapa orang ini punya banyak banget boneka? Aku mulai baca ya.
Melly dengarkan ya, nanti kita gentian bacanya!”
Kurang
lebih seperti itulah saya berbicara sendiri agar tidak ada kesunyian di antara
kami. Harapan saya, Melly serupa dengan anak-anak lainnya yang tidak mau
berbicara di tempat belajar dan kemudian “terpancing” untuk berbicara setelah
saya menjadi cerewet, banyak bercerita.
Sayangnya,
usaha saya belum menunjukkan hasilnya. Melly tetap diam. Bahkan tidak ada satu
katapun yang keluar dari mulutnya. Selama pertemuan ini, Melly hanya memainkan
tangannya. Memasukkan seluruh jarinya ke mulut, mengayunkan badannya ke depan
dan belakang, atau memonyongkan mulutnya.
Mungkin
saya kurang menarik baginya, atau memang pendekatan saya yang salah? Saya
mencoba menerka-nerka. Dan saya tidak bisa menemukan jawabannya.
Pertemuan-pertemuan
selanjutnya saya variasikan dengan bermain, menonton video, dan bernyanyi.
Meskipun tidak membuahkan hasil, saya terus mencoba. Bahkan saya mulai
bercakap-cakap dengannya –meskipun itu hanya seperti berbicara sendiri. Saya
bertanya apapun tentang dirinya meskipun
saya sudah tahu jawabannya dan saya menjawab pertanyaan saya sendiri. Saya
berbicara apa saja yang memiliki hubungan antara saya dan dirinya.
“Waktu aku
sekolah esde, aku gak bisa nulis huruf “a” loh, Mell. Aku coba nulis huruf “a”
botak tapi jadinya aneh banget. Gak mirip huruf “a”. Sediiih banget. Padahal
kalau disuruh nulis, pasti banyak banget kan huruf “a”-nya. Aku belajar nulis huruf
“a” sampe satu buku tulis ini nih, Mell. Pernah juga kertasnya sampai bolong
gara-gara aku selalu ngehapus huruf “a” yang salah. Tapi sekarang aku udah bisa
nulis huruf “a”. Soalnya aku coba terus, Mell.”
Melly tetap
diam hingga satu setengah jam yang berlalu terasa sangat melelahkan dan membuat
saya tampak terlalu bodoh sebagai seorang guru.
(bersambung)