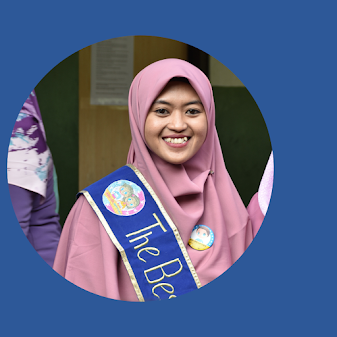Archive for August 2014
Kalau Aku Cinta ...
Pekan lalu, saat aku sedang mengajar matematika di kelas.
Tiba-tiba muridku, seorang anak dengan autisme dan ADD (Attantion Deficite Disorder) menghampiri. Menyentuh daguku dan
memalingkan wajahku ke arah wajahnya. Ada yang ingin disampaikannya dan aku
harus memperhatiannya. Begitulah kurang lebih yang ingin dikatakannya melalui
caranya mendekatiku.
“Ibu …,” katanya sambil menyentuh daguku dengan tangan
mungilnya.
Biasanya sebelum sempat aku menjawab, anak ini akan langsung
membicarakan hal yang akan disampaikan atau ditanyakan. Pertanyaan yang
ajukannya pun selalu disampaikan dengan pola yang sama. Persis sama meski hal
yang ditanyakannya berbeda. Dan semuanya harus berpola sebab-akibat. Misalnya
pertanyaan, “Aku ngantuk, kenapa?”; “Makananku berantakan, kenapa?”; “Tulisanku
tidak muat di buku, kenapa?”, dan banyak lagi pertanyaan yang berakhir tanya ‘kenapa?’.
Lalu anak ini akan bertanya, “Makanya aku jangan apa?”
Tepat sesuai dugaanku, anak surga yang satu ini melanjutkan
perkataannya sambil memalingkan wajahku ke wajahnya, tanpa menungguku menyahut.
“Kalau aku cinta Salsabila, kenapa?” ucapnya dengan intonasi
dan kalimat khasnya.
“Kamu cinta Salsabila?” aku balik bertanya padanya. Sedikit
terkejut mendengarnya.
“Kalau aku cinta Salsabila, kenapa?” dia mengulang tanyanya
dengan intonasi yang persis sama dan mata yang menatapku semakin lekat.
“Ibu jawab nanti ya, Sayang. Kita belajar dulu,” jawabku
sambil memberikan buku tulisnya.
Tanpa menjawab, dia langsung mengambil buku tulisnya dan
kembali ke mejanya sambil terus bergumam. ‘Kalau aku cinta Salsabila, kenapa?’
Sejujurnya, aku bingung mau menjawab pertanyaannya dengan
apa. Anak lelaki usia sembilan tahun dengan autisme dan ADD yang dimilikinya
membuatku sempat berpikir mungkin dia sedang meniru ucapan di tivi. Atau meniru
ucapan teman-temannya di lingkungan sekolah. Entah.
Yang ada dalam pikiranku selanjutnya adalah bagaimana kalau
anak ini bertanya ‘makanya jangan apa?’. Gubrak! Bisa mati kutu aku dibuat anak
ini.
Pulang sekolah, saat aku sudah melupakan pertanyaannya.
Tetiba dia kembali menanyakan hal yang sama padaku. Dengan cara yang sama pula.
Menyentuh daguku, mengalihkan wajahku ke wajahnya. Lalu menatapku dengan dua
matanya yang lebar dan bersinar. ‘Kalau aku cinta Salsabila, kenapa?’
Selalu saja begini. Hampir seluruh muridku yang mempunyai
keautistikkan memiliki ingatan yang sangat tajam. Sampai hal kecil yang luput
dari perhatian dan ingatanku pun tetap diingatnya.
Huhf! Sambil menghembuskan napas dengan agak berat, aku
memutar kepala dan berpikir cepat. Jawab apa ya kira-kira untuk anak ini. Oke. Asumsiku
anak ini mungkin sedang puber dan dia memang sedang tertarik dengan salah satu
temannya.
But … what should I
say to him? O God!
Akhirnya aku bertanya kepadanya. “Kenapa kamu cinta
Salsabila?”
“Kalau aku cinta Salsabila kenapa?” dia kembali mengulang
pertanyaannya tanpa menjawab pertanyaanku.
“Tidak kenapa-kenapa, Sayang,” jawabku sambil mengelus
kepalanya.
“Aku cinta Salsabila, Bu Lisfah,” katanya.
“Oke. Sesama manusia memang
harus saling mencintai, Sayang. Itu artinya kaliam berteman. Tidak
saling bertengkar dan menyakiti. Sama seperti ibu yang mencintai kamu sebagai
murid ibu. Sama seperti umi dan abi di rumah yang mencintai kamu sebagai anak.
Kamu juga begitu. Tidak hanya ke Salsabila. Kamu juga harus mencintai
teman-teman yang lain, mencintai hewan, dan tumbuhan. Karena kita memang harus
mencintai semua makhluk, tidak merusak atau menyakitinya ya.”
“Kalau aku cinta Salsabila, kenapa?” dia kembali bertanya.
“Tidak apa-apa. Kamu harus cinta pada semuanya,”
Lalu dia pergi sambil memainkan jari-jarinya dan tanpa bergumam sepatah kata.
Cuma begitu responnya. Simple. Selalu sesimpel itu di depan
anak-anak. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti dia. Tetiba aku
teringat salah satu bagian di film Cinta Brontosaurus; dalam hal cinta kadang
kita harus menjadi anak kecil yang mencintai tanpa sebab apa-apa.
Argh, seperti ada yang baru di hatiku. A little thing that
belonging breath. More than love.
Jadi, sepertinya lebih asik kalau aku cinta… seperti
anak-anak saja.
Tanpa sebab apa-apa. Hanya cinta.
Tanpa Lilin
Mentari sudah tenggelam beberapa menit lalu. Giliran cercahan
cahayanya yang merekah di balik barat. Langit sudah berubah jadi nila, jingga, lalu merah. Itu saja. Lalu perlahan berubah jadi gelap.
Aku mgnintip ke timur. Mencarinya yang kutahu dia pasti tak ada lagi malam ini. Tidak akan ada bulan malam ini. Sebab purnama sudah pergi lebih dari tujuh hari.
Kala aku memalingkan wajah ke pucuk-pucuk pohon, tetiba kulihat ia terbit. Lagi. Di depanku.
Aku mgnintip ke timur. Mencarinya yang kutahu dia pasti tak ada lagi malam ini. Tidak akan ada bulan malam ini. Sebab purnama sudah pergi lebih dari tujuh hari.
Kala aku memalingkan wajah ke pucuk-pucuk pohon, tetiba kulihat ia terbit. Lagi. Di depanku.
Seperti melihatnya sekali lagi. Purnama datang
menghampiriku. Kini dalam sosok asing yang nyaris tak kukenal.
Lalu kenapa kau bisa mengenal itu purnama?
Sebab ada pendar cahaya yang datang bersamanya. Cahaya yang tak pernah dimiliki satu makhluk Tuhan lainnya di dunia.
Lalu kenapa kau bisa mengenal itu purnama?
Sebab ada pendar cahaya yang datang bersamanya. Cahaya yang tak pernah dimiliki satu makhluk Tuhan lainnya di dunia.
Dari balik rerimbun, aku mengintip wajahnya. Tanpa berkata. Persis seperti gadis yang
malu-malu aku mencoba mengenalnya tanpa bahasa.
Pertama melihatnya tujuh hari sebelum purnama pada malam
itu, aku tahu dia akan datang. Lagi. Entah kapan. Entah kini. Entah sama atau
beda rupa.
Apa yang membuatmu bergitu mudah mengenalnya?
Aku tak pernah tahu apakah dia makhluk Tuhan yang selama ini kupuja; purnama. Tapi saat itu aku merasakan satu hal; tulus.
Bersambung...,
Ngarai Hati Mandalawangi (5)
Tak ada cara
terbaik untuk mengenal siapa orang yang ada di samping kita selain sebuah
perjalanan. Sama halnya tak ada tempat terbaik untuk mengenal siapa diri kita
sebenarnya selain alam lepas.
Empat tahun lalu,
Mr. G, guru bahasa Inggrisku di SMA mengucapkan dua kalimat di atas. Sampai
saat ini, dua kalimat itu tetap kuingat dan kuresapi setiap ada kesempatan
melakukan perjalanan jauh untuk menikmati alam. Dan setiap kali kesempatan itu
datang, aku selalu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Mr. G saat aku masih
mengenakan seragam putih abu-ibu itu adalah benar.
Seperti pada
perjalanan kali ini. Aku ingin mengenal tujuh orang asing yang bersamaku dari
setiap langkah yang akan membawa kami ke tengah hutan dan langit biru yang
membentang. Seperti pada perjalanan kali ini. Aku akan kembali mengenal siapa
diriku sendiri. Mengukur keegoisan dan menakar kesabaran.
***
Aku, dua
sahabatku, dan tujuh orang asing yang baru kukenal akhirnya memuai pendakian.
Dari Green Ranger, kami berjalan beriringan. Menapaki jalan aspal yang tadi,
saat kami lewati beberapa jam lalu masih lengang dan hanya satu dua warung yang
buka, kini sudah ramai. Dipenuhi lalu lalang penduduk asli Cibodas dan beberapa
pendaki seperti kami.
Di akhir jalan
aspal ini kami menikung ke kanan, menapaki jalan dari bebatuan yang disusun
rapi. Menuju jalan setapak yang dipagari dan bersisian dengan lapangan hijau
berumput yang mengarahkan kami pada pintu masuk Taman Nasional Gunung Gede
Pangrango. Di pintu masuk inilah, lebih tepatnya di pos pemeriksaan, kami
berhenti untuk pertama kali untuk menyerahkan surat perizinan.
“Andhika? Berapa
orang?” tanya seorang bapak dari balik kaca di pos pemeriksaan setelah membaca
surat perizinan yang diterimanya.
“Iya, Pak. Sepuluh
orang,” jawab Dhika yang lagi-lagi menjadi orang yang sibuk mengurus kami.
Tidak sampai dua
menit kami di pos pemeriksaan, kami melanjutkan perjalanan menuju pemberhentian
selanjutnya. Aku kurang hapal berapa pos tepatnya di Jalur Cibodas ini. Beberapa
tempat yang kuingat justru tempat pemberhentian yang lebih sering digunakan
untuk peristirahatan para pendaki seperti Telaga Biru, Panyangcangan, Air
Panas, Kandang Batu, dan Kandang Badak.
Setelah melewati
pos pemeriksaan, kami tetap berjalan beriringan. Saling berdekatan sambil
sesekali berbincang. Di sepanjang perjalanan dari Pos Pemeriksaan sampai Panyangcangan,
biasanya ada aliran air di sisi kiri pendaki yang hendak naik. Kali ini aliran
itu kering. Bagi yang belum pernah menaiki Gede-Pangrango melalui jalur Cibodas
mungkin tidak akan tahu kalau sebenarnya ada air yang mengaliri parit di sisi
jalan.
Setelah beberapa
menit melangkah, menelusuri parit yang kering, mataku tertuju pada salah satu
papan bertuliskan “Telaga Biru” pertanda kami hampir sampai di tempat
pemberhentian pertama. Teman yang lain mendahuluiku, salah satu di antara
mereka bilang bahwa kita berhenti di Panyangcangan saja yang jaraknya tidak
jauh dari Telaga Biru dan lebih luas daripada Telaga Biru.
Telaga biru sudah
di depan mata. Pos pemberhentian pertama ini adalah sebuah toilet dan tanah
lapang kecil yang di depannya saat itu dipenuhi banyak pengunjung berwajah
oriental yang sedang tertawa terbahak. Aku ikut tertawa melihat tingkah mereka.
Beberapa teman jalan begitu saja, tak menghiraukan apa yang ada di depannya. Di
belakangku ada Yola dan Bang Awal. Aku menoleh ke belakang. Yola sepertinya
memuntahkan cairan. Ya, hanya cairan. Bening. Seperti air.
“Mau lanjut?”
tanyaku pada Yola.
“Lanjut aja,
Teh,” jawabnya dengan wajah yang sudah mulai pucat.
Aku berjalan
bersisian dengan Yola. Saat mendekatinya, bau muntah sudah menyengat hidungku.
“Kamu muntah?
Istirahat dulu ya. Aku bilangin ke yang lain,” kataku sambil memerhatikan
wajahnya yang sudah menunjukkan raut lelah. Saat itu sebenarnya tubuhku juga
sudah merasakan lelah. Payah. Sudah mengantuk meskipun tubuh harus tetap
bergerak.
Beberapa meter ke
depan, kami tiba di Panyangcangan. Lebih banyak pendaki yang berhenti di sini.
Teman-teman yang lain sudah mengambil posisi untuk duduk atau sekadar
bersandar. Aku memilih duduk meluruskan kaki, sambil bersandar di carrierku
sendiri.
“Yola mau minum
obat supaya gak mual?” aku bertanya pada Yola yang berdiri saja di seberangku.
Bersisian dengan Bang Awal dan Dhika.
“Yola muntah?”
tanya Kak Tiwi.
“Cuma air. Tadi
kebanyakan minum,” jawab Yola.
Aku menyodorkan
satu sachet obat herbal cair ke arah Yola. Kemudian aku mengeluarkan satu sachet
madu untuk aku minum sendiri. Ini adalah kali pertamanya aku meminum madu. Saat
itu ketidaksukaanku pada rasa manis harus aku buang jauh-jauh. Tubuhku yang
semakin payah, kepala yang pusing, dan mata yang meminta untuk dipejamkan memaksa
diriku meminum madu.
Aku meminum
sesachet madu dengan menutup hidung dan meminum beberapa teguk air untuk menghilangkan
rasa manis di lidah dengan segera. Di pikiranku saat itu adalah aku ingin
melanjutkan perjalanan tanpa harus menyusahkan orang lain karena fisikku yang sedang lemah. Hanya itu.
Lima menit
setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Kami melewati jembatan
terbentang di sepanjang Rawa Gayonggong. Di jembatan ini kami masih jalan
beriringan. Aku memilih jalan di belakang sambil memerhatikan yang lain
berbincang dan bercengkerama. Mengenal mereka dari jauh.
Jembatan sudah
kami lalui. Setelah ini jalan yang akan kami tempuh akan semakin sulit.
Bebatuan dan tanah yang tersusun tak cukup beraturan. Setelah ini pula para
pendaki akan disuguhi jalan bercabang yang pendek, jalur kanan biasanya jalur
pintas tetapi lebih curam dan sebaliknya untuk jalur kiri yang landai namun
lebih panjang.
Di percabangan
pertama inilah Dhika meminta ransel Yola untuk dibawanya. Mulanya Yola menolak,
tetapi kami memaksanya agar tidak ada beban bawaan Yola dan dia bisa berjalan
lebih cepat lagi. Di sini pula Bang Edi menanyakan apakah aku ingin bertukar
tas dengannya, sebab tasku paling berat dibandingkan teman-teman perempuan
lainnya dan sedikit lebih berat dari bawaan Bang Edi.
“Masih bisa kok.
Minta bantu tarikin di sini aja palingan,” jawabku sambil menunjuk pada jalan
di depan kami yang cukup tinggi.
Di sinilah tim
kami jalan berjauhan. Di depan sana Kak Lina, Sofi, Yudith, dan Dhika sudah
jauh meninggalkan kami. Aku, Erni, Kak Tiwi, Bang Awal dan Bang Edi jalan di
belakang. Kala itu Yola mulai menunjukkan ketidaksanggupannya. Kak Tiwi juga
tetiba meminta kami agar berjalan lebih pelan. Tubuh Yola dan Kak Tiwi sudah
basah kuyup oleh keringat, padahal kami belum menempuh separuh jalan yang harus
kami lalui untuk menuju Kandang Badak. Ini pertanda tubuh dua teman kami sedang
payah.
Sepanjang jalan
ini kami benar-benar terpecah. Aku dan Erni memutuskan jalan lebih dulu bersama
Yola. Kak Tiwi berjalan di belakang kami, ditemani Bang Edi dan Bang Awal. Aku
dan Erni sering berhenti menunggu Kak Tiwi, Bang Edi, dan Bang Awal, sambil
menemani atau lebih tepatnya memaksa Yola untuk beristirahat.
Aku kembali
mencium bau muntah. Sekali lagi aku dan Erni bertanya pada Yola. “Kamu sakit?
Istirahat dulu ya. Mau makan?”
Lagi-lagi jawaban
Yola tidak, kecuali untuk beristirahat. Duduk sejenak. Sejujurnya, kala itu
yang aku rasakan adalah sendiri. Ya. Benar-benar sendiri. Aku merasakan
pendakian kali ini benar-benar berbeda dengan pendakianku selama ini.
Dulu, saat aku
masih duduk di bangku SMP –setiap pendakian meskipun itu hanya ke Gunung Bunder
atau Gunung Salak, pun di bangku SMA saat masih aktif di Pecinta Alam, para
senior selalu meneriakkan hal yang sama. Liatin
temen yang di belakang, masih ada apa nggak! Naik gunung jangan egois! Gak
bakal kabur gunungnya! Saling jagain temen! Semuanya saling tanggung jawab sama
timnya!
Kalimat-kalimat
sejenis itu selalu aku ingat. Sampai saat ini. Bahkan di masa-masa aku tidak
lagi berhubungan dengan aktivitas alam. Seorang penikmat alam akan tahu dirinya
tidak boleh egois. Karena masih ada tanah, angin, dan api yang bisa sekali
waktu menghabisi dan tidak bisa dihindarinya. Seorang penikmat alam akan tahu dirinya
harus jauh dari kesombongan. Sebab ada gunung-gunung perkasa yang siap
memuntahkan isinya atau menggelindingkan siapapun yang mendakinya, ada lautan
berombak tinggi yang kapan saja bisa menggulung kapal sebesar apapun bersama
isinya, dan ada hamparan padang pasir mematikan siapapun yang terjebak di dalam
luasnya.
“Baru pertama
kali gue naek kayak begini,” seruku saat kami bertiga melanjutkan perjalanan.
“Kenapa
emangnya?” tanya Erni.
“Gak enak. Pada
mencar-mencar. Gak mikirin ada temennya yang sakit,” aku jujur.
“Iya sih. Beda
sama biasanya ya. Biasanya kan kita tetap deketan jalannya. Saling tunggu. Saling
jaga,”
“Nah itu dia. Gue
merasa di sini naeknya buat have fun aja. Gak ada rasa ngejagain temen. Gak
nganggep tim-nya ada,” aku sedikit naik pitam.
“Orang-orangnya
juga gak asik. Gue mau balik aja nih rasanya,” Erni menimpali sambil membantu
Yola melangkah.
“Orang-orangnya
gak asik mungkin karena kita emang belom pada kenal. Tapi justru karena belom
kenal harusnya kita punya tanggung jawab yang lebih. Apalagi katanya udah ada
yang sering naek. Masa gak respect sama kondisi temen sih?” aku kembali berargumen.
Kemudian kami
saling diam. Menunggu Yola yang beristirahat sambil menunggu Kak Tiwi, Bang
Edi, dan Bang Awal.
***
Tatkala kami
berenam sudah bersama, kami berjalan berdekatan. Mencoba mempercepat langkah.
Siapa tahu kami bisa mengejar yang lainnya di depan.
Pada sebuah
persimpangan jalan menanjak, sebuah pohon melintang di jalan. Kak Tiwi, dan
Erni berjalan di depan. Aku mempersilahkan Yola jalan mendahuluiku, sedangkan
Bang Edi dan Bang Awal tepat di belakangku. Tetiba sebuah suara muncul dari
depan.
“Ini dia. Makan
dulu, Wi!” entah siapa yang berbicara demikian. Aku lupa.
Beberapa teman
sudah membuka nasi. Sepertinya mereka sudah cukup lama duduk dan baru saja
membuka bekal makan siang. Kak Tiwi, Erni, dan Yola duduk bersisian dengan Yudith,
Kak Lina, dan Shofi. Sedikit ke depan, ada Dhika. Aku berhenti dan meletakkan
tas lebih rendah daripada tempat duduk Dhika.
“Jalannya pada
mencar-mencar banget ya. Kasihan yang di belakang, yang sakit, ketinggalan
jauh!” aku menumpahkan kesal yang entah didengar atau tidak oleh yang lainnya.
Saat itu semuanya sedang sibuk dengan makan siang masing-masing.
Aku duduk
menghadap arah kedatangan kami. Minum dan melepas lelah, juga amarah.
“Fatin, sini.
Makan siang dulu!” Kak Tiwi memanggilku.
Aku tidak
menjawab. Hanya menghampiri dan mengambil sebungkus nasi berserta lauknya yang
disodorkan Kak Tiwi dalam sebuah kantung plastik. Yang lainnya menikmati makan
siang sambil bersisian atau saling berhadapan dan sambil berbincang. Aku
memilih duduk di atas sebuah potongan batang pohon, menghadap hutan lebat dan
makan sendirian. Bukannya aku tidak ingin melebur atau berbaur, aku hanya ingin
sendiri. melepas kesal dan ketidaknyamananku di perjalanan ini.
“Fatin sendirian
aja. Sini gabung!” seru Yudith kepadaku.
“Udah pewe,”
hanya itu jawbaku.
Aku masih makan
kala yang lainnya sudah hampir selesai dan beberapa di antaranya sudah selesai
makan dan bersiap melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi, beberapa di antara kami,
terutama Kak Lina, Yudith, dan Shofi, bersiap dan jalan terlebih dahulu seperti
tak memikirkan yang lainnya. Aku dan Erni yang sebelumnya sudah sepakat akan
berjalan bertiga saja dengan Yola pun memutuskan berjalan belakangan. Menunggu
Yola yang masih bersiap. Dhika berjalan di belakang kami. Kak Tiwi, Bang Edi,
dan Bang Awal lebih di belakang, tak jauh jaraknya.
Selepas makan
siang ini, aku benar-benar hanya jalan bertiga dengan Erni dan Yola. Sesekali
kami berbarengan dengan Dhika yang kadang mendahului, membelakangi, atau
beriringan dengan kami. Sedangkan Kak Tiwi tetap dengan Bang Awal dan Bang Edi.
Terkadang, sambil menemani Yola beristirahat, Kak Tiwi bisa mengejar langkah
kami.
Selepas makan
siang ini pula, aku menyempatkan diri untuk tidur dua kali kala Yola meminta
istirahat. Lima sampai sepuluh menit terpejam di pinggir jalan, sambil
meluruskan kaki dan bersandar pada carrier cukup mengurangi kepayahan tubuh
ini. Semilir angin, kicauan burung, dan gemercik air yang terdengar samar-samar
juga membantuku mengurangi bad mood
yang menjejal di kepala.
Kami hampir tiba
di Air Panas. Aku, Erni, dan Yola, menunggu Kak Tiwi, Bang Edi, dan Bang Awal
yang masih di belakang kami. Kala itu Dhika sudah berjalan lebih dulu. Mengejar
Kak Lina, Shofi, dan Yudith.
“Jam berapa
sekarang?” tanya Kak Tiwi kepadaku sebelum kami menjejaki bebatuan, melewati
aliran air panas yang deras.
“Hampir jam 2,”
jawabku menerka, setelah melihat matahari dan bayangan yang dibentuknya.
“Shalat di depan
aja ya,” kata Kak Tiwi, memutuskan dna mengabarkan pada Bang Awal yang ada di
depan kami, “Bang Awal, di depan kita berhenti ya. Shalat dulu.”
Aku, Kak Tiwi,
dan Erni berwudhu di aliran air hangat berbau belerang. Kemudian naik ke
dataran yang lebih tinggi, mencari tanah datar, kemudian shalat zuhur dan ashar
yang dijamak. Yola yang sedang tidak shalat menunggu di dekat kami. Bang Edi
dan Bang Awal menceburkan diri ke aliran air hangat. Menyegarkan badan dan
memilih menjamak shalat di waktu ashar.
Ketika kami
selesai shalat, Dhika sudah berdiri di dekat kami. Mengajak kami untuk bergegas
dan bergabung dengan yang lainnya yang menunggu tak jauh dari kami. Aku memilih
diam. Tak menjawab sepatah pun karena masih ada rasa kesal. Kak Tiwi mengiyakan
dan bergegas menuju tempat yang lainnya menunggu.
Aku, Erni, Kak
Tiwi, dan Erni membuntuti Dhika. Disusul oleh Bang Edi dan Bang Awal di
belakang kami. Ternyata Kak Lina, Shofi, dan Yudith, menunggu di tanah kosong
di belakang Air Panas. Lokasi peristirahatan yang biasanya digunakan pendaki
untuk membuat minuman hangat atau beberapa pendaki yang pernah kutemui biasanya
juga mendirikan tenda di sini.
Sesampainya di
tempat yang lainnya menunggu, Bang Awal dan Bang Edi melanjutkan menceburkan diri ke aliran air hangat yang
ada di depan kami. Sayangnya, belum ada semenit aku, Erni, Kak Tiwi, dan Yola
tiba, berkumpul bersama mereka, ternyata Kak Lina, Shofi, dan Yudith, sudah
bersiap untuk melanjutkan perjalanan.
“Lanjut yuk!”
kata Yudith, didahului Shofi yang sudah menggendong carriernya.
“Kelamaan
berhenti. Kaki jadi sakit,” sambung Kak Lina yang ikut berdiri dan bersiap
untuk melanjutkan perjalanan.
Aku tercengang.
Merasakan suasana dongkol yang kembali berjejal.
“Gila! Ngapain lu
pada nyuruh kita nyamperin kalo lu bakal jalan nafsi-nafsi gini?” aku bergumam
dalam hati.
“Lanjut?” tanya
Dhika pada kami yang baru tiba.
“Terserah. Gue
sih lanjut hayuk. Istirahat dulu hayuk. Mending tanya Yola aja tuh!” jawabku
sambil berusaha menyembunykan kekesalan.
Seperti yang
sudah kuduga, mereka tidak akan bertanya pada kami apakah kami ingin lanjut atau
beristirahat barang sejenak. Mereka langsung jalan. Entah mereka tahu atau
tidak bahwa Yola dan Kak Tiwi sedang dalam kondisi payah. Pun itu sebenarnya
aku juga.
Beberapa menit
setelah mereka berjalan, Bang Awal dan Bang Edi sudah selesai memanjakan diri mereka
dengan aliran air hangat. Kami melanjutkan perjalanan. Jarak Kandang Badak dari
tempat kami beristirahat tidak terlalu jauh. Kami tinggal melewati Kandang
Batu, sebuah tanah lapang yang berdekatan dengan air terjun lebar yang juga
sering dijadikan pilihan tempat mendirikan tenda oleh beberapa pendaki,
kemudian kami harus melewati jalan bebatuan hingga kami menemukan jalan berbatuan
pipih tersusun rapi dengan pepohonan lebat. Setelah kami melewati semua itu,
barulah kami akan tiba di Kandang Badak.
Saat kami sudah
menjejaki jalan setapak dengan bebatuan pipih tersusun rapi, Dhika berjalan
mendahului kami. Dia hendak menyusul yang lainnya. Aku berjalan bersisian
dengan Erni, Kak Tiwi dan Yola di belakangku, disusul Bang Edi dan Bang Awal.
Kami hampir
memasuki memasuki Kandang Badak saat Dhika berjalan ke arah kami. Dia
menunjukkan arah tempat yang lainnya berkumpul. Akhirnya, kami pun berkumpul.
Utuh, setelah sejak melewati Panyangcangan kami berpisah seperti bukan satu tim
perjalanan.
“Lanjut atau mau
diriin tenda di sini? Masih kuat?” tanya Dhika kepadaku yang bersandar pada
pohon.
“Kalau badan
kuat. Tapi mata ngantuk,” ujarku
“Gue juga. Di
sini aja gak apa-apa ya,” jawab Dhika.
Saat itu
sebenarnya semangatku untuk berkemah benar-benar menghilang. Setibanya di
Kandang Badak, aku merunduk pada carrier yang sudah kulepas, memejamkan mata
hingga tanpa sadar aku kembali terlelap.
Aku terjaga, kala
sebuah tangan mengguncang carrier yang menjadi tempatku menyandarkan kepala. Ternyata
yang lainnya sudah tidak ada. Mereka sudah menuju tempat kami akan mendirikan
tenda. Shofi yang dibuntuti Dhika sedang berjalan di depanku. Dengan wajah
lesuh, tubuh yang semakin payah, mata yang sudah tidak bisa diajak kompromi,
dan bad mood yang semakin menjadi aku
berjalan mengikuti mereka menuju lokasi kemah.
Setibanya di
lokasi kemah, ketidaknyamananku semakin menjadi. Aku mengeluarkan logistik,
kompor, dan sarungtangan. Erni yang ada di sampingku pun melakukan hal sama.
“Lisfah, gak
enak,” katanya dengan suara nyaris berbisik.
“Suasananya ya?
Sama. Baru pertama kali naek gak enak banget kayak gini,” aku menanggapi dengan
suara sama rendahnya. “Rasanya sekarang gue pengin balik aja,” aku melanjutkan.
“Besok pagi balik
yuk! Gak usah muncak. Berdua aja. Berani kan?” kata Erni.
“Berani. Tapi
liat nanti malam sampe besok pagi. Kalo suasananya masih ngedongkolin kayak
gini, mending gue balik besok pagi,” jawabku.
“Iya,” seru Erni
sambil membantuku mengangkuti beberapa barang yang harus dikumpulkan di dapur
yang kami buat.
Kandang Badak
semakin gelap. Pertanda matahari sudah beristirahat, bergantikan malam,
berkawan udara yang semakin dingin di kulit muka. Tapi suasana hati yang
kurasakan tetap sama. Jengkel, marah, dan ingin lenyap saja di antara mereka.
Sebenarnya, hal
paling membuatku tidak nyaman adalah sikap Shofi yang selalu menempel dengan
Dhika. Sebentar-sebentar yang dipanggil Dhika, pun itu sebaliknya. Seperti
tidak ada orang lain yang dikenalnya di antara kami. Seperti yang lain tidak ada
dan hanya ada mereka berdua. I don’t know they are a couple or not, tapi sikap
mereka –yang teman-temanku yang pacaran pun tidak seperti itu, membuat aku
mengeluarkan satu kata untuk mereka berdua. Norak!
A, sudahlah!
Whatever about all of they are did. Those not my matters.
Aku, Erni, dan
Kak Lina shalat maghrib digabungkan dengan shalat isya berjamaah dengan Bang
Awal. aku, Erni, dan Kak Lina, Selepas itu, aku menghampiri yang lainnya yang
sedang menyiapkan makan malam. Semua pekerjaan sudah diambil alih. Saat aku
hendak membantu pun tidak ada yang benar-benar merespon. Alhasil, aku
memutuskan diam. Berdiri saja dekat pohon.
Kak Lina
berjongkok di sampingku. Lama posisi kami berdua seperti ini. Hingga tanpa
diduga, Bang Awal datang menghamparkan sebuah matras dan menyuruh kami duduk di
atasnya.
“Nggak. Berdiri
aja,” aku menolak ajakan Kak Lina untuk duduk. Hingga yang lainnya ikut
menyuruhku untuk duduk.
Lama aku berdiri
hingga memutuskan untuk ikut duduk, merapatkan lutut ke dada. Lalu memutarkan
pandangan ke sekeliling Kandang Badak dan pucuk-pucuk pepohonan yang gelap.
Tanpa kutahu bagaimana mulanya, aku baru menyadari kala Erni menyentuh
pundakku, membangunkanku yang tengah tertidur bersandar di pundak Kak Lina.
“Bangun, Lis.
Makanannya hampir matang,” kata Erni.
“Nggak mau
makan,” jawabku sambil bangkit, berlalu menuju tenda dan melanjutkan memejamkan
mata.
Kak Lina yang
ternyata juga tertidur saat duduk, mengikutiku ke dalam tenda. Kami pun tidur
lebih dulu. Mungkin Kak Lina lelah, setelah mengebut dari bawah ke Kandang
Badak. Tapi aku, selain memang ingin membayar hutang tidur yang tersita selama
lima hari belakangan, memilih tidur adalah agar aku bisa lekas melewati malam.
Agar segala kekesalan, bad mood, dan
segala emosi juga perasaan yang entah bisa segera hilang dan bisa aku lupakan.
Dan yang paling penting adalah tidak akan ada yang jadi korban dari kekesalanku
malam itu.
Sebelum
benar-benar memejamkan mata di dalam tenda, aku sempat teringat salah satu
ajaran Rasulullah. Bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengangkat
beban paling berat atau berpetualang ke tempat yang paling jauh. Bahwa orang
yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya.
Aku terdiam
sejenak. Mencoba merefleksikan ucapan Rasulullah pada diriku sendiri di saat
itu. Aku tersenyum, menyunggingkan senyuman itu untuk diriku sendiri. Bodoh!
Kataku pada diriku sendiri, mengingatkan apa gunaku marah pada mereka yang baru
kukenal.
Buat apa lu marah sama orang yang sangat mungkin
gak tau kalau dirinya berbuat kesalahan. Toh kesalahan itu mungkin cuma berlaku
di mata lu, bukan di mata orang lain. Sekali lagi aku berseru pada diriku sendiri.
“Lisfa, dingin,”
suara Erni membuyarkan lamunanku. Tubuhnya sudah menghambur di dekatku.
“Sini dipeluk
biar hangat. Pake sleeping bag berdua nih yuk. Ini masih bisa dishare kok,”
jawabku dengan suasana hati lebih tenang.
“Makan aja dulu
yuk! Kak Lina juga, makan dulu yuk!” kata Erni disusul ajakan makan dari teman
lainnya yang ada di luar tenda.
“Ngantuk. Capek,”
kata Kak Lina.
“Nggak ah. Mau
tidur aja. Kak Lina dingin juga? Mau dipeluk gak?” kataku sambil membuang
sedikit kejengkelanku yang juga tertuju pada Kak Lina.
Erni dan Kak Lina
tertawa mendengar jawabanku.
Kak Lina
merapatkan sleeping bag-nya, melanjutkan istirahatnya.
“Besok pagi jadi
turun duluan?” bisik Erni, lebih pelan dari percakapan kami berdua setiba di
Kandang Badak.
“Liat mood
besok,” jawabku sambil menyeringai.
“Ah, dasar!” Erni
mulai mengencagkan suaranya. “Lisfah beneran gak makan? Gue makan duluan ya.
Yaah, gak ada yang nemenin gue makan dong!”
“Yang laen kan
banyak,” jawabku sambil menutup sleeping bag, meletakkan lengan di atas
cekungan mata, lalu terpejam dengan suasana hati sedikit membaik.
Kejengkelanku, sedikit terkikis.
Aku tidak pernah tahu apa
yang akan terjadi esok hari. Yang aku tahu adalah aku harus tetap melangkah ke mana
pun arahnya, menikmati dan belajar dari alam yang selalu menjaga dirinya untuk
tetap seimbang.
Bersambung…,
05 August 2014
Posted by Lisfatul Fatinah
.jpg)