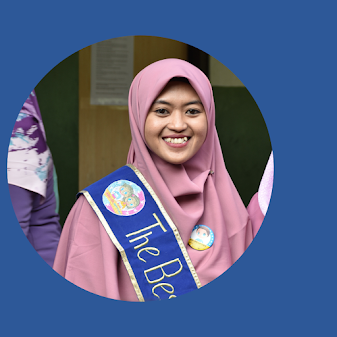Archive for April 2014
Kenapa Ibu Merobek Kertas?
Kasat matanya, saya menuangkan apa yang saya punya pada mereka dan
mereka menerima saja. Tapi nyatanya, cawan saya tak pernah kering meski isinya
terus dituang dan mereka lebih jujur dalam melihat realita.
~Guru Pendidikan
Khusus dan Murid Istimewanya~
 Menjalani aktivitas sebagai guru pendidikan khusus bukan
sekadar mengajar dan transfer ilmu yang saya dapatkan sejak SD hingga kuliahan.
Menjadi guru pendidikan khusus, bagi saya lebih mirip seperti menelusuri alam.
Menjalani aktivitas sebagai guru pendidikan khusus bukan
sekadar mengajar dan transfer ilmu yang saya dapatkan sejak SD hingga kuliahan.
Menjadi guru pendidikan khusus, bagi saya lebih mirip seperti menelusuri alam.
Kenapa begitu? Ya, setiap memegang satu anak istimewa sama
seperti sebuah perjalanan menelusuri satu hutan atau mendaki gunung menjulang.
Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita temukan dalam lebat dan luasnya
rimba. Kita tak pernah tahu apa yang bersembunyi di balik kelokan jalan setapak
di antara barisan belukar. Pun kita tak bisa mengira kapan sungai mengarus
deras dan siap menyeret kita.
Menjadi guru bagi mereka istimewa, bagi saya adalah tentang
satu kata: KEJUTAN.
Jika imba membawa saya pada arti keberadaan Allah SWT. dalam
keindahan. Maka pendidikan khusus dan anak-anak istimewa menggiring saya pada arti
keberadaan Allah SWT dalam keindahan yang berbeda.
Salah satu keindahan yang saya temukan di dunia istimewa ini
adalah kejadian kecil yang akan saya bagi saat ini. Mungkin ini hanya kejadian
kecil yang teramat sepele. Tapi ia dapat menampar saya habis-habisan hingga
saya terpekur dalam malu.
Setiap mengajar, saya punya kebiasaan membawa buku-buku anak
dari rumah. Buku-buku ini milik KOPAJA yang sengaja saya manfaatkan dengan
membacakannya atau membaca bersama anak-anak di kelas. Setiap hari, saya akan
membawa buku yang beda. Meskipun hanya 10-15 menit sebelum pulang, aktivitas
membaca “buku baru” harus selalu saya dan anak-anak lakukan.
Pagi kemarin, setelah anak-anak, terutama salah satu murid
istimewa saya mengerjakan tugasnya, saya mengajaknya membaca buku yang saya
bawa. Judul bukunya “Aku Anak Baik di Sekolah”, sebuah buku anak terjemahan
yang sudah saya pelajari sebelumnya.
Setiap halaman buku berisi gambar kondisi guru dan
murid-muridnya. Di lengkapi dengan 2-3 kalimat sederhana yang menjelaskan
tentang gambar di tiap halaman. Salah satu halaman menggambarkan suasana kelas
yang kacau dan tenang.
Pada gambar kelas yang tenang, semua anak duduk manis dengan
tugas mereka atau sambil mambaca. Sedangkan pada gambar kelas yang kacau, semua
anak melakukan aktivitas semaunya. Ada yang menumpahkan air minum, mencoret
meja, merobek buku, dan mengobrol.
Tiba saatnya saya berbicara. Saya mengucapkan satu
pernyataan yang teryata menyeret saya pada kekonyolan di hadapan murid saya.
“Jadi, mencoret meja, mengobrol saat guru menjelaskan, dan
merobek buku itu perbuatan yang tidak baik yaaa!” seru saya dengan suara agak
keras.
Lalu muncul satu celoteh. “Ibu, kenapa robek buku tidak baik?”
“Karena buku dibuat untuk menulis atau dibaca, bukan
dirobek,” jawab saya.
“Kalau dirobek memangnya kenapa?” anak saya melanjutkan
tanyanya.
“Kalau dirobek, bacaannya tidak lengkap. Tulisan kamu bisa
hilang. Daaan…, bisa mengotori kelas,” jawab saya lagi masih dengan keadaan
pede.
“Tapi. Tapi kenapa ibu robek buku?” anak ini menghantam
saya.
“Hah?” saya terkejut. “Ibu tidak robek buku. Ibu robek
kertas untuk bikin bebek. Untuk kita belajar matematika.” Saya memang kerap
kali membawa keras berwarna untuk membantu saya menjelaskan beberapa pelajaran
kepada anak-anak.
“Bukaaaaan,” tangannya mengibas-kibas di depan wajah. “Dulu
ibu pernah robek buku tulis!”
“Kapan ya itu?” saya meletakkan telunjuk di kening sambil
bergaya sedang mengingat danberpikir sungguh-sungguh. Sejujurnya, saat itu saya
benar-benar sedang berpikir keras kapan saya pernah merobek buku di hadapan
anak-anak.
Ternyata ingatan saya lebih membela murid saya. Saya memang
pernah merobek buku di hadapan murid istimewa saya. Saat lupa untuk alasan apa
saya merobek buku tersebut, terlebih di hadapan murid. Tapi semua itu sudah
terjadi, permasalahannya bagaimana saya meluruskan apa yang diterjemahkan murid
ini saat mengingat saya merobek buku di depannya.
“Oh ya. Waktu itu ibu merobek kertas. Berarti ibu sudah
bersikap salah dan tidak baik. Kalian tidak boleh meniru ibu,” jawab saya pada
salah satu murid istimewa saya yang lebih seperti jawaban diplomatis.
Ini kejutan baru di perjalanan mengajar anak-anak istimewa.
Siapa yang mengira anak yang dijastifiksi sebagai anak disleksia (punya
kelemahan berupa kecerobohan sehingga berpengaruh pada kemampuannya mengingat).
Tapi dengan mengejutkan, anak ini bisa mengingat hal kecil
yang saya lakukan dan “menegur” saya di saat yang sangat tepat. Terlalu tepat
malah kalau saya pikir. Ya, meskipun ini
membuat saya malu dan bingung. Apakah anak ini memahami jawaban “Saya sudah
melakukan kesalahan dan tidak baik untuk ditiru”. Semoga saja.
Setidaknya dari pengalaman ini saya belajar untuk lebih
menjaga sikap di hadapan anak-anak. Termasuk saat saya berbicara. Karena kendati
mereka mereka berbeda dan lebih dikenal sebagai anak yang “lebih bodoh” dari
anak umumnya, nyatanya mereka bisa secerdas itu protes atas sikap saya.
Di balik kejadian kecil dan dialog sederhana ini, setidaknya
saya mengerti menjadi guru –terlebih guru pendidikan khusus –tidak akan pernah
habis menuangkan ilmu dan kasih yang saya punya. Karena sebanyak itu semua yang
saya keluarkan, sebanyak itu pula saya mendapatkannya lagi, bahkan lebih.
Lebih istimewanya lagi, sama seperti alasan mengapa saya senang
ada di antara anak-anak. Begitu pula alasannya saya senang ada di antara mereka
yang istimewa. Mereka jujur dan polos dalam melihat dunia kita.
Mereka polos menilai saya. Berkata apa adanya pada saya. Mereka
tidak menggunakan azas “enak-nggak enak”
saat menegur saya yang berposisi sebagai guru mereka. Mereka dengan polosnya
mengatakan apa yang memang seharusnya mereka katakan. Dan saya selalu senang
dengan hal ini. Dan saya selalu menanti kejutan lainnya lagi.
Hingga Kita
"Teman yang baik bisa membuatmu nyaman namun juga tega berbicara keras dan mendorongmu keluar dari kenyamanan yang tidak baik"
(anonim)
Setidaknya itulah yang sejatinya selama ini aku lakukan dengan maksimal pada orang-orang yang aku anggap sebagai sahabatku. Bahwa aku bisa menjadi orang yang paling nyaman untuk berbagi suka dan duka sekaligus tega menegurnya dengan caraku ketika orang yang aku anggap sahabat berbuat salah.
***
"Kemana kamu sebenarnya sejak Sabtu-Selasa?" tanya aku
tanpa basi basi melalui What's App.
"Ke rumah nenek," jawabnya singkat.
"Kenapa kamu harus berbohong?" kembali aku bertanya.
"Itu aku sudah jujur!" jawabnya seperti geram.
"Iya aku tahu. Tapi kenapa baru sekarang jujurnya?"
Dia dan aku terdiam.
"Apa yang kamu cari?" lanjut tanyaku padanya.
"Perhatian," singkat sahutnya.
"Kamu sudah dapat perhatian yang kamu inginkan?" tanyaku
lagi.
"Nggak," jawabnya lalu aku kembali diam.
Ini adalah sepenggal percakapan terakhirku dengan salah seorang
yang aku anggap sahabat. Dia adalah satu dari empat orang hebat yang aku kenal
hampir empat tahun ini.
Di akhir percakapan itu, ingin rasanya saat itu aku bertanya,
"Kurangkah kita memberi perhatian kepadamu? Dapatkan aku dan kita memberi perhatian yang kamu harapkan?" Tapi sayangnya, pertanyaan ini tak pernah
aku lontarkan sejak percakapan itu ada hingga dirinya -dengan caranya yang tak
kukenal- memintaku untuk diam.
Semua percakapan di atas bermula dari sebuah firasat yang datang
tiba-tiba pada Jumat, 4 April 2014. Hari itu, tanpa alasan yang jelas, tetiba
aku memiliki firasat yang kurang baik padanya. Aku seperti kehilangan satu dari
empat sahabat yang aku punya. Karena kekhawatiran itu, di hari yang sama aku
mengirim pesan kepada tiga sahabatku yang lainnya. "Sering ngobrol dengan
dia? Tahu kabarnya saat ini?"
Tiga sahabatku yang lain menjawab sama,
"Jarang. Tidak tahu."
Dua hari sejak kekhawatiran itu muncul, sebuah kabar dari salah
satu di antara kami datang padaku. "Dia cuti sampai hari Selasa. Pergi
dari rumah sejak Jumat dan tidak mengabari kepergian dan cutinya pada orang
rumah. Umi baru tahu dia cuti dari murid-muridnya." Kurang lebih begitulah
pesan yang aku terima melalui What's App.
"Aku ingat dia bilang mau ke Puncak bareng teman kampusnya.
Coba aku cek dulu ke teman kampusnya. Mungkin dia ke Puncak sampai
Selasa," jawabku setelah mengingat penggalan percakapan di kali terakhir
pertemuanku dengannya.
"Kelasku gak ngadain agenda jalan-jalan pekan ini, Lis,"
balas seorang teman yang aku kenal sebagai teman sekelasnya.
Selepas membaca pesan dari teman sekelasnya, semakin besar tanya
dalam benakku. Semakin terpilih gelung kekhawatiran di hatiku. Lalu aku
berinisiatif bertanya pada seorang teman lainnya yang aku kenal sebagai senior sekaligus kakak angkatnya semasa sekolah.
"Dia bilang mau ke Pulau Seribu bareng teman-teman di al-
Azhar," bunyi pesan yang kuterima beberapa menit selepas aku bertanya.
Pesan yang terbaru ini membuatku semakin bertanya, "Kemana
dia sebenarnya?" Lalu kekhawatiran semakin menjadi dalam diri hingga aku kembali
berinisiatif untuk bertanya pada seorang seniorku -dan dia- di kantor majalah
tempat kami pernah bekerja dan kini aktif di al-Azhar.
"Setahuku memang ada rihlah (red. jalan-jalan). Tapi gak tahu kemana dan
hanya sampai Ahad. Aku gak tahu banyak tentang rihlah itu, Lisfa, habisnya aku
gak diajak sih. Huhuhu," jawab seniorku dengan gaya humorisnya.
Seperti mati rasa pada canda, aku malah melanjutlan tanyaku
padanya dengan semakin serius. Hingga percakapan antara aku dan seniorku ini
lagi-lagi berakhir dengan tanya yang semakin bercabang dan kekhawatiran yang
semakin besar. Kemudian kecurigaan muncul kala aku teringat pada cerita satu di
antara kami berlima.
"Dia sudah sebegitu dekatkah dengan Abang pulang
seberang?" tanya itu terlempar kala aku hanya berdua dari lima di antara
Kita.
"Entahlah. Aku juga gak tahu. Dia gak pernah cerita apapun
lagi," jawabku apa adanya.
"Aku khawatir sama dia. Aku takut dia melenceng dari yang
seharusnya," suara sahabat di depanku menunjukkan gelisah. Air mukanya
berubah jadi muram.
“Kenapa?” tanyaku dengan dada yang refleks berdebar semakin
kencang.
Kemudian sahabat yang ada di depanku menceritakan perubahan sikap
sahabat kami yang menjadi kekhawatiran kami beberapa pekan lalu. Semua
diceritakannya dengan ragu dan ketakutan, sekaligus kecewa yang terpendam.
“Mungkin kau salah lihat. Coba dicek lagi nanti,” aku mencoba
menetralkan perasaan.
“Aku sudah lihat jelas-jelas. Aku lihat berulang. Sampai aku
mengucek mata berkali-kali karena awalnya aku harap pengelihatanku salah,”
jawabnya gelisah.
“Kau pulang saja dulu. Istrahat. Kita lihat lagi nanti. Semoga
yang kau lihat itu salah,” jawabku sambil memukul ringan jok motornya. Sementara itu aku berperang dengan pikiranku sendiri untuk mengiyakan atau tidak berita
mengecewakan yang dikabarkan.
Yang menjadi perbincanganku dengan sahabatku ini aku anggap
sebagai aib sahabatku yang lain yang juga akan menjadi aibku sendiri. Oleh
sebab itu aku tidak akan menceritakannya di sini secara gamblang. Tapi yang
jelas ini adalah hal yang sangat mengecewakanku sebagai salah seorang yang
menganggapnya sahabat dan ingin dia selalu dalam kebaikan.
Karena perbincangan inilah aku sempat menghubungkan hilangnya
kabar dariya dengan perihal yang membuat kami diam-diam kecewa padanya. Semua itu
refleks mengalir bersama khawatir, kecewa, dan curiga yang berkulum jadi satu
di tengah kegentingan kami untuk menunggu kabar yang sebenarnya darinya.
Kekhawatiranku -termasuk kekhawatiran yang lainnya- bertambah
ketika sebuah kabar datang dari Umi tentang sikapnya yang bertolak belakang
dari apa yang selama ini kami kenal. Belum lagi perihal kebohongan yang kami
dengar dari orang lain. Lalu dirinya yang semakin tertutup dan perlahan menjauh
membuat kami seakan diasingkan. Aku tak mengenal lagi sosok yang dulu pernah menemaniku berjalan berkilo-kilo meter jauhnya dan berpetualang dengan ransel ke berbagai
tempat di Jawa hingga Sumatera.
“Mungkinkah Umi berbohong?” tanyaku pada salah satu di antara
Kita.
“Aku yakin Umi tidak berbohong,” jawab sahabatku di seberang sana
melalui What’s App.
“Berarti dia berbohong kepada kita? Kenapa?” jawabku dengan kecewa
yang semkin dalam.
“Entah. Mungkin kita sebenarnya bukan siapa-siapa baginya,” jawab
sahabatku dengan kecewa yang sudah bercampur marah.
Dialog ini lagi-lagi membuatku gamang. Oh Tuhan mengapa seperti
ini? Sungguh mengerikan satu kebohongan yang terungkap ternyata membuat
kebohongan-kebohongan lainnya terungkap. Semua ini tidak aku harapkan. Semua ini
sangat tidak ingin aku ketahui.
Beberapa hari selanjutnya, dalam grup What’s App yang berisi kami
berlima, kami saling berbalas puisi persahabatan. Bukan tentang persahabatan
mengembirakan. Puisi-puisi yang ada, termasuk dariku, adalah puisi-puisi
kesedihan tentang persahabatan yang memudar. Tentang ikatan yang mengendur dan
kenangan yang mulai dilupakan.
Hingga aku mengirimkan salah satu syair lagu yang semasa SMA
sering aku nyanyikan dan kerap menjadi “alat” pembangkit semangat ketika aku
sedang berjauhan dengan sahabat-sahabatku.
Dulu
kita sahabat
Teman
begitu hangat
Mengalahkan
sinar mentari
Dulu
kita sahabat
Berteman
bagai ulat
Berharap
jadi kupu-kupu
Kini
kita melangkah berjauh-jauhan
Kau
jauhi diriku karena sesuatu
Mungkin
kuterlalu bertingkah kejauhan
Namun
itu karena KUSAYANG
“Ada apa ini sebenarnya? Yang kalian maksud itu saya?” untuk
pertama kalinya dia muncul di grup setelah berhari-hari tak ada kabar dan
meninmbulkan kekhawatiran dan kecewa pada kami.
Aku pribadi menjadi lebih sedih saat kalimat itu muncul dengan
penggunaan kata “saya”. Tak pernah aku mendengarnya menggunakan kata "saya" untuk
berbincang dengan kami. Tapi kalimat itu, yang baru saja dikirimnya di grup,
membuatku semakin asing dan jauh dari sosoknya yang dulu.
“Kok kamu ngomongnya begitu? Ini tentang KITA, bukan tentang aku
atau kamu saja,” jawabku setelah sedikit menenangkan hati.
Tak ada jawaban darinya.
Perbincangan kami pun berlanjut hingga satu di antara kami
menginisiasi untuk jujur. Maka di hari itu, semua postingan berisi tentang
kejujuran kami semua.
Cukup lama kami saling membalas kejujuran hingga aku sempat
menangis karena kejujuran yang ditulisan beberapa sahabat lainnya. Semuanya
berlangsung dengan cepat tanpa ada postingan apapun darinya.
Kemudian entah bagaimana jadinya salah satu dari kami, sahabat
yang mengabarkan berita kecewa kepadaku, langsung membahas permasalahan tentang
kebohongannya. Sebuah postingan darinya membalas pertanyaan spesifik
tentangnya. Postingan itu singkat, sangat singkat. Karena itu aku semakin
merasa asing dengannya. Belum lagi sebaris kalimat tanya yang dikirimnya, “Ada
lagi?”
Aku tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Yang ada di benakku
adalah, “Dia bukan sahabat yang aku kenal selama ini.” Lalu perbincangan
memanas. Terutama antara dia dengan salah seorang di antara kami.
"Kemana kamu sebenarnya sejak Sabtu-Selasa?" tanya aku
tanpa basi basi melalui What's App di luar grup kami berlima.
"Ke rumah nenek," jawabnya singkat.
"Kenapa kamu harus berbohong?" kembali aku bertanya.
"Itu aku sudah jujur!" jawabnya seperti geram.
"Iya aku tahu. Tapi kenapa baru sekarang jujurnya?"
Dia dan aku terdiam.
"Apa yang kamu cari?" lanjut tanyaku padanya.
"Perhatian," singkat sahutnya.
"Kamu sudah dapat perhatian yang kamu inginkan?" tanyaku
lagi.
"Nggak," jawabnya lalu aku kembali diam.
Lalu pertanyaanku yang selanjutnya dijawabnya seolah-olah dia
berkata, “Diam! Jangan banyak tanya lagi! Kamu bukan siapa-siapaku!”
Sontak setelah itu aku memutuskan untuk diam dengan diam yang
sesungguhnya. Tak lagi bertanya, tak lagi menyapa, tak lagi mengirim jujur. Hingga
akhirnya, diam semakin diam dengan sebuah kiriman tulisan panjang dari dirinya
melalui salah satu di antara kami.
Tak banyak yang aku ingat tentang tulisan itu, sebab terlalu sakit
yang aku rasa saat itu atas apa yang disampaikannya. Bagiku, sebagai salah
seorang yang menjadi tujuan tulisan itu, kalimat “kamu bagai wartawan gossip”, “kamu
tak punya hak untuk tahu”, “kamu tidak pernah bertanya kenapa aku begini”
adalah kalimat yang benar-benar membuatku terpental jauh dari masa-masa yang
selama ini aku lewati bersamanya. Yang menambah kepedihan ini adalah bagaimana bisa tulisan itu datang tidak langsung dari dirinya. Mengapa melalui orang lain. Tidakkah itu malah semakin menyakitkan.
Semua tulisan itu sungguh menghancurkan senyum dan harapanku atas hubungan kami. Isi tulisan itu sungguh membuatku mengerdil, seakan dia membuangku dengan jijik ke tong sampah yang sangat dalam. Menyedihkan!
Semua tulisan itu sungguh menghancurkan senyum dan harapanku atas hubungan kami. Isi tulisan itu sungguh membuatku mengerdil, seakan dia membuangku dengan jijik ke tong sampah yang sangat dalam. Menyedihkan!
Dari tulisan itu setidaknya aku kembali berpikir dan bertanya
pada diriku sendiri, “Benarkah selama ini kami saling bersahabat? Apakah
selama ini aku yang terlalu pede menganggapnya sahabat padahal dia tidak
menganggapku sahabatnya. Atau lebih buruk lagi, mungkinkah selama ini aku
bukanlah siapa-siapa baginya?”
Aku mengkhawatirkannya, lantas mengapa dia menjawab kekhawatiran ini dengan cara seperti itu? Aku hanya tidak ingin dia berbohong. Lalu mengapa seolah-olah kami yang kecewa pada kebohongannya adalah pihak yang salah. Aku hanya ingin dia dalam koridor ajaran Tuhan. Tapi mengapa dia menganggap aku tidak berhak mencampuri urusannya, meski aku tahu yang telah dilakukannya salah. Aku hanya ingin memperhatikannya, hanya ingin menjadi pengganti dari perhatian orang-orang yang dianggapnya tidak perhatian padanya -meskipun aku tahu semua yang ada di rumahnya adalah orang yang sayang padanya. Tapi mengapa aku diminta diam olehnya.
Akhirnya, untuk terakhir kalinya hingga saat ini aku memosting di
grup kami berlima tentang jujur dan maafku pada orang-orang yang selama ini aku
anggap sahabat, padahal mereka belum tentu menganggapku sahabatnya.
Aku hanya bisa memohon maaf karena selama ini aku telah terlalu
pede menganggap mereka sahabatku. Aku hanya bisa meminta maaf atas caraku menegur atau khawatir dianggap sebagai kekasaran dan mengganggu. Apalagi hingga
aku dilabelkan sebagai “Wartawan Gosip”. Aku hanya bisa memohon maaf atas
kekhawatiranku pada orang-orang yang aku anggap sahabat dan aku ingin mereka tetap
dalam koridor ajaran Tuhan yang malah dianggap kelancangan. Aku hanya bisa
berdoa semoga mereka, terutama dia, punya orang-orang yang dianggapnya sebagai
sahabat yang bisa melihatnya keluar dari koridor ajaran Tuhan dan hanya diam
saat dirinya berbuat salah.
Sejujurnya, tak ada yang aku inginkan dari sebuah persahabat
kecuali sebuah hubungan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran juga saling
mendorong agar kami bisa semakin dengan Tuhan. Perihal apa yang telah
aku lakukan dengan mencari tahu kabar kebenaran dari berbegai pihak hanya untuk
memastikan bahwa yang aku dengar dari mulutnya adalah benar. Tapi ternyata kabar-kabar dari
berbagai pihak itu malah mengirim kabar kekecewaan bagiku, bahwa aku
mendengarkan kabar yang salah darinya. Bahwa aku mendengarkan kabar kebohongan darinya. Lalu bertambahlah sedih, khawatir, dan kecewa dalam dada.
Tak ada benci atau amarah dalam hatiku. Semua itu hanya termaktub di bibir tanpa sedikitpun ada di hati. Tapi sedih itu tetap bersemayam dalam diriku atas sebuah kesadaran bagaimana seorang yang aku anggap sahabat malah
menganggapku sebagai “wartawan gossip”, “orang yang tidak berhak
mengingatkannya ketika salah”, “orang yang tidak berhak menegurnya ketika dia
jauh dari koridor yang sesungguhnya kami jaga bersama di atas ajaran Tuhan”.
Memang kebohongan adalah hal yang paling sulit kuterima. Apalagi dengan
sikap protektifku pada diri sendiri -yang kerap kali membentengi diri dari dunia
luar- sangat sulit menerima hal-hal yang sudah aku ketahui sebelumnya sebagai
kebohongan. Tapi aku berpikir dan merajuk diri sendiri untuk memberi sedikit
kelonggaran pada orang yang sudah dekat denganku hampir empat tahun ini dan
sudah kuanggap sebagai sahabat sekaligus saudaraku sendiri.
Tapi sungguh, itu semua tidak cukup mudah. Bagai memperbaiki gelas
yang sudah pecah. Seperti apapun pecahan itu disambung, tatap ada retak yang
tampak. Tetap ada garis putus yang tak tersambug lagi dan gelas itu tak mampu menampung
air sebaik dulu lagi.
Seperti ikatan yang aku rasakan ini. Meski maaf sudah terberi dari
hati, semua itu tetap tidak bisa berulang. Butuh waktu untuk mengembalikannya
seperti semua. Bukan dengan menambal retakan atau menyambung pecahannya,
melainkan harus dibuat dari mula. Membangunnya lagi dari nol berbekal
pengalaman yang sudah dirasakan sebelumnya.
Hingga saat ini, aku masih memikirkan dia dan tiga lainnya yang
aku anggap sahabat –entah sebagai apapun mereka menganggap diriku. Masih aku
kirimkan doa untuk Kita, agar Tuhan saja yang memautkan rasa dan mengikat hati Kita.
 |
| Kita yang kini telah menjadi aku, kamu, dan dia |
Semoga ada waktu di mana kita kembali bersama dengan sikap
yang lebih dewasa, lebih saling jujur, lebih saling terbuka, lebih memberi perhatian hingga tak ada satu di antara kita yang kebingungan mencari perhatian, lebih saling
memahami tanpa ada ragu dan benci yang dipendam diam-diam hingga membusuk dan
membuat yang lainnya ikut busuk hingga menghancurkan yang nyaris utuh.
Meski ada sakit dan masih sering menitikkan air mata jika
mengingat masa-masa genting itu, aku tetap yakin ini adalah skenario
terbaik-Nya untuk menunjukkan bahwa aku menyayangi kalian dengan caraku dan
kalian menyayangi dengan cara kalian. Bahwa kita saling memperhatikan dengan cara yang berbeda.
Andai kalian tahu, diam-diam aku ingin membangun kembali bangunan hati yang pernah pecah ini. Diam-diam aku menuliskan kerinduanku pada 15 April 2014 lalu untuk kalian dalam bahasa Jepang yang aku rangkai menggunakan kamus bahasa Jepang di smartphone-ku.
Shoujiki na: watahi wa aibo suru atsui yojou desu.
Jujur: Aku merindukan kehangatan persahabatan itu.
Andai kalian tahu, diam-diam aku ingin membangun kembali bangunan hati yang pernah pecah ini. Diam-diam aku menuliskan kerinduanku pada 15 April 2014 lalu untuk kalian dalam bahasa Jepang yang aku rangkai menggunakan kamus bahasa Jepang di smartphone-ku.
Shoujiki na: watahi wa aibo suru atsui yojou desu.
Jujur: Aku merindukan kehangatan persahabatan itu.
Semoga kalian baik-baik di sana.